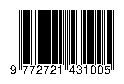Model Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Durensewu Pandaan
Abstract
Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting dalam upaya peningkatan taraf hidup, terutama di kawasan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis efektivitas model kolaborasi pemberdayaan masyarakat berbasis pengolahan pangan di Desa Durensewu. Model ini mengintegrasikan peran masyarakat lokal, pemerintah, dan stakeholder terkait untuk menciptakan ekosistem agribisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk pangan bernilai tambah. Selain itu, model ini juga membuka peluang pasar yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pengolahan pangan berbasis kolaborasi dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk itu, diperlukan penguatan pelatihan teknis, dukungan kebijakan pemerintah, dan pendampingan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan program.
Full Text:
PDFReferences
Istilah “pemberdayaan masyarakat” sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari – hari. Istilah ini tidak lagi asing bagi kita mengingat banyaknya program pemberdayaan masyarakat yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial atau kemasyarakatan, hingga pihak swasta (Alhada et al., 2021). Informasi mengenai program –program tersebut kerap kita temui di berbagai media masa, seperti koran, radio, televisi, dan internet. Umumnya, program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Konsep pemberdayaan berasal dari kata daya berarti kekuatan dan merupakan terjemahan dari istilah “empowerment”. Secara umum, pemberdayaan mengacu pada proses memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok yang kurang berdaya atau belum mampu mandiri, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan (Harahap, 2018). Kelompok yang kurang berdaya buka hanya di perkotaan juga terdapat di pedesaan. Fenomena, masyarakat desa yang tidak memiliki lahan pertanian akibat penguasaan lahan oleh pengusaha untuk perumahan ataupun pabrik. Masyarakat desa kehilangan mata pencaharian sebagai pemilik tanah atau bertani pada sawah miliknya sendiri menjadi buruh lepas.
Tabel 1. Produksi Buah – Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis tanaman di Kecamatan Pandaan (kuintal), 2020 -2023)
Jenis Tanaman 2020 2021 2022 2023
Blimbing 398 169 16 24
Jambu Biji 910 4.413 116 110
Mangga 40.123 55.495 1.645 8.708
Pepaya 8.231 7.693 2.797 3.792
Pisang 5.961 7.576 995 1.087
Rambutan 180 385 97 173
Sumber: BPS Pandaan, 2024
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Kecamatan Pandaan merupakan penghasil komoditas buah buahan: blimbing, jambu biji, mangga, pepaya, pisang, rambutan. Komoditas yaitu mangga pada urutan pertama pada tahun 2020 sebesar 55.495 kuintal namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 8.708 kuintal (BPS, 2024). Komoditas yang dimiliki Pandaan berpotensi dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku olahan produksi pangan.
Desa Durensewu terletak Kec Pandaan, Kab Pasuruan. Luas desa ini 3,34 km2 terdiri dari 7 dusun, 7 RT, dan 46 RW. Luas tanah tanaman pangan, sawah 212,00 tegal 9,13 bangunan dan pekarangan 108,54. Kepadatan penduduk 1,946.11 per km2. Jumlah penduduk laki-laki 3,288 jiwa dan perempuan 3,212 jiwa. Jumlah penduduk 6500 jiwa (Pasuruan, 2023). Dengan jumlah penduduk perempuan yang tidak jauh beda dengan laki-laki. Mata pencarian rata-rata penduduk Durensewu adalah pertanian yang tergantung dengan musim, dan karakteristik lahan/sawah. Namun banyak lahan pekarangan/tegal yang dibiarkan dengan tanaman buah dan tanaman liar lainnya. Lahan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk tanaman yang bermanfaat bagi keluarga, misal mangga untuk manisan.
Desa yang terletak di kaki Gunung Arjuno ini memiliki sumber daya alam yang menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Salah satunya tempat wisata yaitu: Makoya, Telaga Sewu, Wisata Durensewu dan Taman K-land. Suatu daerah menjadi tempat destinasi wisata akan diikuti hotel, vila, homestay, restoran dan kafe. Wisatawan akan membelanjakan sejumlah uang untuk membiayai selama liburan. Kendati demikian, kondisi ini belum menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat. Keterlibatan masyarakat di sekitar pariwisata ini juga belum optimal.
Desa ini dikenal dengan keberagaman sumber daya alam yang dapat menjadi basis untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, seperti banyak desa lain di Indonesia, Durensewu masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Tantangan tersebut meliputi: Desa Durensewu belum memiliki pasar, kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan, keterbatasan peluang kerja, serta rendahnya daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Selanjutnya bagaimana konsep kemitraan strategis yang dilakukan desa Durensewu. Tujuan penelitian ini mengetahui kemitraan yang dilaksanakan desa Durensewu dan unsur-unsurnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pendekatan kolaborasi yang tepat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendekatan kolaborasi yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat di desa Durensewu.
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan model pemberdayaan masyarakat yang efektif, berbasis kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan terciptanya sinergi yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi desa, meningkatkan keterampilan, dan membuka akses pasar secara lebih luas.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan fenomologi yang memahami sudut pandang pemikiran, pengalamam para stakeholder mengenai kemitraan strategis upaya pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di desa Durensewu, Kec Pandaan Kabupaten Pasuruan. Jenis data pada penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan primer dan sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan informan yang mengetahui dan terlibat dalam pemerintahan desa. Informan pada penelitian ini: Kepala desa, pamong desa, pelaku usaha kuliner, akademisi, dan masyarakat. Data dianalisis melalui tahap yaitu pengkodean, pengkategorian, reduksi, dan penyajian data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial. Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang menitikberatkan pada manusia sebagai pusatnya (people-centered), melibatkan partisipasi aktif (participatory), bersifat memberdayakan (empowering), serta berorientasi pada keberlanjutan (sustainable). Dalam konteks ini, ekonomi kreatif menjadi salah satu elemen penting, karena berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat (Alhada et al., 2021), (Agustana, 2020).
Ekonomi pedesaan merupakan suatu sistem sosial-ekonomi yang kompleks dan terdiversifikasi, dibentuk oleh interkoneksi antara objek dan subjek. Struktur ekonomi pedesaan yang terdiversifikasi sebagai suatu sistem yang mampu memobilisasi sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut serta mengembangkan sektor-sektor dan usaha utama mereka, seperti pertanian (baik tradisional maupun modern), non-pertanian (meliputi industri, konstruksi, kehutanan, kerajinan tangan, dan jasa), serta industri jasa (seperti pendidikan, layanan kesehatan, rekreasi, dan ketenagakerjaan). Dengan menggunakan pendekatan tiga cabang, yaitu "fungsi-struktur-tujuan," terciptalah model diversifikasi ekonomi pedesaan yang mencakup beberapa industri dominan atau kombinasi dari berbagai industri yang berbeda (Merenkova et al., 2019)
Beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat Durensewu meliputi, minimnya ketrampilan kewirausahaan, banyak masyarakat masih bergantung pada sektor agraris tanpa adanya diversifikasi usaha. Terbatasnya kolaborasi, sinergi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan komunitas lokal masih belum optimal dalam mendorong program pemberdayaan. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan sebuah model kolaborasi yang mengintegrasikan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, organisasi non-pemerintah, akademisi, komunitas lokal, dan pelaku usaha.
Pembuatan model kolaborasi untuk memberdayakan masyarakat miskin dirancang dengan mengacu pada tiga elemen utama, yaitu: 1) peningkatan kapasitas; 2) hubungan antar-aktor; dan 3) aspek keberlanjutan. Proses penguatan kapasitas masyarakat difokuskan pada perencanaan dan internalisasi nilai-nilai pemberdayaan di kalangan para aktor. Pemberdayaan kolaboratif mencakup mekanisme hubungan antar-aktor dalam berbagai tahapan pengelolaan pemberdayaan, mulai dari identifikasi masalah hingga upaya menjaga keberlanjutan. Model kolaborasi ini mampu meningkatkan efektivitas peran setiap sektor dalam satu agenda pemberdayaan. Kesatuan proses dan kolaborasi peran dapat membentuk modal sosial bagi masyarakat guna mempersiapkan agenda pemberdayaan berikutnya atau program yang berkelanjutan (Suaedi & Widiono, 2018).
Kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pengolahan pangan Di Desa Durensewu. Kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat yang melibatkan tiga pihak utama, pemerintah desa, masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator atau penggerak utama yang menghubungkan masyarakat dengan pelaku usaha. Masyarakat adalah pihak yang diberdayakan berbagai program yang dirancang. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang terdiri dari PKK, Karang Taruna dan organisasi masyarakat lainnya. Pelaku usaha, baik itu UMKM maupun perusahaan besar, menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Usaha menengah kecil khusunya usaha kuliner merupakan usaha yang dilakukan perorangan yang belum atau berbadan hukum.
Menurut Kepala Desa Durensewu menyampaikan penduduk desanya rata-rata mata pencarian sebagai petani. Pendapatan sebagai petani padi yang tidak tentu tergantung dengan panenannya. Tanah pekarangan dan halaman rumah warga kurang dimanfaatkan dengan baik. Kepala desa juga menyampaikan desa memiliki Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) mengelola aset desa untuk bisnis bersama mitra dengan bentuk sewa dalam waktu tertentu. Dengan Bumdes diharapkan dapat menyerap tenaga kerja desa agar tidak ke kota, dan dapat meningkatkan kas desa. Petugas desa juga menyatakan desa Durensewu belum memiliki sentra khusus kuliner. Unit usaha kuliner masih bersifat sporadis artinya menyebar dimana-mana dan belum terkoordinasi dengan baik. Hal serupa disampaikan pedagang kuliner yang datang dari luar daerah, belum adanya komunitas kuliner sejenis apalagi sentra kuliner.
Hal ini serupa disampaikan masyarakat desa Durensewu belum tahu pemberdayaan berbasis pengolahan pangan bila ingin usaha kuliner langsung usaha tanpa pendampingan ataupun pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat. Hasil pertanian rata-rata padi setelah panen gabah dijemur untuk dijual dan sebagian disimpan. Salah satu warga desa juga mengatakan pekarangan warga belum di kelola dengan maksimal banyak lahan kosong, tegalan ditumbuhi buah –buahan mangga, nangka, pete, pohon pisang dan rumput liar. Meskipun desa basis pertanian belum ditemui produk inovasi yang berasal dari bahan lokal, hal itu dibenarkan oleh perangkat desa. Lanjut Kepala desa juga menyampaikan kolaborasi dengan media, Perguruan Tinggi masih minim. Pimpinan desa itu juga menyampaikan membuka diri bila ada perguruan tinggi yang ingin memberikan pelatihan termasuk kuliner kepada warganya.
Pendekatan kolaborasi pemberdayaan masyarakat berbasis pengolahan pangan dengan pendekatan pentahelix. Model pemberdayaan masyarakat dengan basis pengolahan pangan bertujuan diharapkan mengurangi kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektoral. Selama ini masyarakat tani cenderung menjalankan usaha secara parsial dengan teknologi terbatas. Terbentuknya indutri pengolahan hasil pertanian di desa. Diharapkan dapat meningkatkan sistem agribisnis yang dikelola mereka sendiri. Meski demikian diperlukan dukungan dari para pemangku kepentingan diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (Windari, 2021). Proses kolaborasi telah berlangsung dengan baik, yang tercermin dari dialog langsung, peningkatan kepercayaan, komitmen masyarakat, serta pemahaman yang beragam tentang pembangunan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian hasil pembangunan yang efektif, baik secara fisik maupun non-fisik (Antono et al., 2020).
Selanjutnya, Steiner & Farmer, (2018) melakukan penelitian dengan eksplorasi skala besar mengenai proyek pemberdayaan di tujuh komunitas pedesaan di Skotlandia, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat perlu mengadopsi teknik pengembangan komunitas yang melibatkan aktor eksternal dan sumber daya pendukung (praktik eksogen), serta memanfaatkan potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri (praktik endogen). Pentahelix merupakan kerangka untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan pada sektor pariwisata. Pendekatan kolaborasi pentahelix bukan hanya untuk wisata namun diadopsi dapat digunakan sektor lain misalkan sosial ekonomis dalam strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Gambar 1. Pentahelix Pemberdayaan Masyarakat
Model kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses terhadap sumber daya, pasar, serta teknologi. Fandi et al., (2024) menjelaskan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, seperti yang terlihat di kawasan Wisata Geopark Ijen Banyuwangi. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan pariwisata sehingga dapat berkonstibusi meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran.
Pemerintah desa merupakan aktor sentral dalam penyusunan kebijakan, regulasi, dan koordinasi antar pihak (Kirana & Artisa, 2020). Adapun peran pemerintah desa yakni: memfasiltasi kerja sama antara elemen lain, menyediakan anggaran atau akses kepada sumber daya, meningkatkan infrastruktur desa untuk mendukung pemberdayaan (Ahmad et al., 2021), (Prasetyo et al., 2021). Perguruan Tinggi berkonstribusi melalui penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi menyediakan solusi berbasis riset untuk mengembangkan potensi desa. Perguruan tinggi memberikan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Lanjut Perguruan Tinggi membantu menciptakan teknologi tepat guna yang mendukung kegiatan ekonomi lokal. Pelaku usaha, baik skala kecil (UMKM) maupun besar, menjadi mitra dalam mengembangkan ekonomi desa: menciptakan peluang usaha berbasis potensi lokal, memberikan pendanaan, pelatihan bisnis atau akses pasar, mengintegrasikan masyarakat dalam rantai produksi dan distribusi.
Media berperan sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi, edukasi, dan promosi kegiatan pemberdayaan. Media meningkatkan kesadaran tentang potensi dan peluang desa. Mendokumentasikan program pemberdayaan untuk meningkatkan kepercayaan pihak luar. Media, membantu memasarkan produk-produk lokal melalui platform digital dan konvensional. Masyarakat adalah subyek utama yang diberdayakan. Adapun peran masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan. Mengoptimalkan potensi lokal seperti sumber daya alam, budaya atau kerajinan. Mengelola hasil program untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial desa.
Hubungan kolaborasi Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah desa mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menyusun program pemberdayaan yang sesuai. Pemerintah desa menciptakan regulasi yang mempermudah pelaku usaha untuk terlibat dalam pemberdayaan. Pelaku usaha dan masyarakat, pelaku usaha memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan penyediaan pasar. Pemerintah desa dan perguruan tinggi, kerjasama untuk merancang program berbasis riset. Perguruan Tinggi dan pelaku usaha, kolaborasi dalam mengadopsi inovasi dan teknologi di sektor bisnis lokal.
Penguatan koordinasi antar elemen pentahelix dan diperlukan koordinasi yang intensif antara perguruan tinggi, pelaku usaha, media dan masyarakat untuk memastikan setiap pihak memahami peran masing - masing dalam pemberdayaan melalui forum diskusi atau pertemuan berkala dapat menjadi sarana untuk menyamakan visi dan tujuan. Peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat sebagai subyek utama pemberdayaan perlu dilatih dan diberdayakan secara berkelanjutan. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengadakan pelatihan ketrampilan, manajemen usaha, dan literasi digital untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program. Agar program lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, masyarakat harus lebih dilibatkan dalam tahap perencanaan (Molosi & france et al., 2020). Partisipasi aktif akan meningkatkan rasa memiliki terhadap pemberdayaan sehingga dapat berkelanjutan.
Desa Durensewu memiliki Perguruan Tinggi yaitu vokasi kuliner diharapkan berkonstrbusi dalam pengembangan desa melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pangan. Perlu adanya kolaborasi Pemerintah desa dengan Perguruan Tinggi untuk pengolahan hasil pertanian menjadi produk yang bernilai jual. Pemerintah desa dapat melibatkan perguruan tinggi dalam diskusi upaya menggali pemikiran dari para akademisi. Masyarakat menyediakan bahan baku untuk diolah di kitchen yang dimiliki perguruan tinggi dan digunakan memasak mahasiswa praktek. Perguruan tinggi memberikan produk inovasi berupa resep untuk diadopsi masyarakat. Pengembangan model kolaborasi pentahelix ini belum cukup namun diperlukan pula komunikasi antar sektor sehingga program yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat sebagai obyek maupun subyek dalam pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan yang bekelanjutan.
SIMPULAN
Pendekatan model pentahelix ini diperlukan implementasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendekatan ini dalam pemberdayaan masyarakat desa menciptakan kolaborasi yang sinergisitas antara berbagai pihak. Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, mandiri, dan berbasis potensi lokal melalui kontribusi masing-masing. Kolaborasi lima elemen yakni: Pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, Perguruan Tinggi, dan media tidak hanya meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa tetapi juga memperkuat keberlanjutan program melalui pembagian tanggung jawab dan manfaat yang merata. Dengan demikian, pendekatan pentahelix dapat menjadi model yang ideal untuk diterapkan dalam berbagai konteks pembangunan masyarakat, khususnya di desa. Implementasi yang baik dari pendekatan ini memerlukan komunikasi yang kuat, koordinasi yang berkesinambungan, evaluasi program secara berkala untuk memastikan berkeberlanjutan dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat dapat memanfaatkan waktunya dengan baik, ketika menunggu panen padi dengan membuat karya atau sesuatu bernilai atau dijual menghasilkan tambahan penghasilan. Perguruan Tinggi melakukan pengabdian sebagai bentuk tanggung jawab para akademisi kepada masyarakat dengan workshop, pelatihan dan kegiatan lainnya.
UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada Kepala Desa, perangkat, dan masyarakat Durensewu yang berkenan memberikan informasi penting yang berguna terhadap artikel ini. Dan semua pihak terkhusus LPPM Akademi Sages yang memfasilitasi penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Agustana, P. (2020). Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial. Locus, 12(1), 60–69. https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.288
Ahmad, Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 114–124. http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi
Alhada, M., Habib, F., Kunci, K., Masyarakat, P., Kreatif, E., Bumdesa, ;, Peningkatan, ;, Pemberdayaan, E. ;, & Masyarakat, E. (2021). KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF. |, 106(2), 2776–7434. http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index
Antono, A., Setiahadi, M., & Ngalimun, N. (2020). Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan Melalui Program Dana Desa Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 8(2), 102–108. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.17
BPS. (2024). Kecamatan Pandaan Dalam Angka.
Harahap. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In De La Macca (Vol. 01, Issue 1).
Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 68–84. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119
Merenkova, I., Smyslova, O., & Kokoreva, A. (2019). Development models of rural areas: Theoretical approaches and formation specificity. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 341(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/341/1/012017
Molosi-France, K., & Dipholo, K. (2020). Empowering Botswana’s rural communities through the Sustainable Livelihood approach: Opportunities and constraints. ASEAN Journal of Community Engagement, 4(2), 342–359. https://doi.org/10.7454/ajce.v4i2.1101
Pasuruan, B. P. S. K. (2023). Kecamatan Pandaan Dalam Angka 2023. https://pasuruankab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/ea6b98086a36b6ddf9400a90/pandaan-subdistrict-in-figures-2023.html
Prasetyo, E., Utami, P., & Aulia Amanda, T. (2021). Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 7(3), 276–296. https://doi.org/10.26618/kjap.v7i3.6298
Steiner, A. A., & Farmer, J. (2018). Engage, participate, empower: Modelling power transfer in disadvantaged rural communities. Environment and Planning C: Politics and Space, 36(1), 118–138. https://doi.org/10.1177/2399654417701730
Suaedi, F., & Widiono, G. W. (2018). Collaborative Community Empowerment Model to Improve the Living Quality of Poor People - Case Study on “Down-Syndrome Village” in Ponorogo Regency. 1(Icse 2017), 362–366. https://doi.org/10.5220/0007098403620366
Windari, W. (2021). ****PMD Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Produksi Di Pedesaan Community Empowerment Model In Production-Based Local Economic Development Effort in Rural Areas. Jurnal Agirekstensia, 20(1), 90–106.
DOI: https://doi.org/10.30596/jisp.v6i2.22276
Refbacks
- There are currently no refbacks.